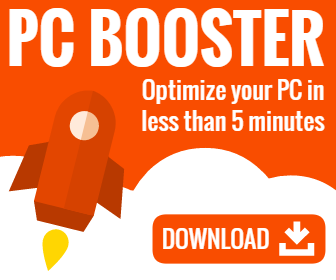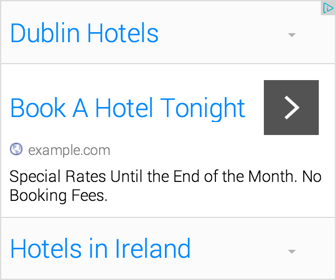Oleh: Suwidodo
Kitabaru.com, Jakarta – Otonomi daerah yang efektif berjalan sejak awal 2000-an—dan secara luas sejak 2003—lahir dari semangat besar reformasi: mendekatkan pelayanan publik, memeratakan pembangunan, dan memutus rantai sentralisme kekuasaan ala Orde Baru. Secara konsep, otonomi daerah adalah koreksi sejarah. Namun setelah lebih dari dua dekade berjalan hingga 2025, muncul pertanyaan mendasar: mengapa di tingkat paling bawah, khususnya kelurahan dan desa, justru marak terjadi korupsi?
Pada masa Orde Baru, kekuasaan bersifat sentralistik. Jakarta menjadi pusat hampir seluruh pengambilan keputusan. Daerah hanya pelaksana. Korupsi tentu ada—bahkan sistemik—namun terkonsentrasi pada elite pusat dan segelintir elite daerah. Rakyat kecil jarang bersentuhan langsung dengan anggaran, apalagi ikut menentukan arah kebijakan.
Otonomi daerah mengubah lanskap itu secara radikal. Dana mengalir deras ke daerah: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, hingga Dana Desa. Kelurahan dan desa yang dulu “miskin kewenangan” kini memegang anggaran yang tidak kecil. Sayangnya, perubahan struktur kekuasaan ini tidak diikuti dengan perubahan kualitas sumber daya manusia dan integritas aparatur di tingkat bawah.
Inilah paradoks besar otonomi daerah: kekuasaan diturunkan, tetapi integritas tidak ikut naik.
Di banyak kelurahan dan desa, dana publik dikelola oleh aparatur yang minim kapasitas administrasi dan lemah pemahaman tata kelola keuangan. Sistem pengawasan internal sering kali formalitas. Lembaga pengawas lokal—seperti BPD atau LPM—tidak jarang justru terkooptasi oleh relasi kekerabatan, kepentingan politik, atau budaya ewuh pakewuh. Akibatnya, penyimpangan dianggap hal biasa, bahkan “risiko jabatan”.
Korupsi pun berubah wajah. Jika dulu berskala besar dan terpusat, kini ia menyebar, kecil-kecil, namun masif dan mengakar. Mark-up proyek, laporan fiktif, proyek titipan tim sukses, hingga penyalahgunaan bantuan sosial menjadi praktik sehari-hari. Ironisnya, semua terjadi di ruang yang paling dekat dengan rakyat.
Faktor lain yang memperparah keadaan adalah politik biaya tinggi. Pemilihan kepala desa atau lurah—baik langsung maupun tidak—sering menelan ongkos besar. Ketika seseorang terpilih, jabatan bukan lagi amanah pelayanan, melainkan sarana “balik modal”. Dalam situasi seperti ini, anggaran publik dipersepsikan sebagai hak penguasa lokal, bukan milik rakyat.
Apakah ini berarti otonomi daerah gagal? Tidak sepenuhnya.
Otonomi daerah berhasil membuka ruang demokrasi, mempercepat pembangunan lokal, dan mendorong inovasi daerah. Banyak daerah maju justru karena kewenangan yang luas. Namun otonomi daerah gagal membangun fondasi etika, integritas, dan sistem pengawasan yang kuat di level akar rumput.
Kesalahan terbesar reformasi bukan pada desentralisasi kekuasaan, melainkan pada asumsi bahwa kekuasaan otomatis akan dikelola dengan baik ketika didekatkan ke rakyat. Padahal, tanpa pendidikan politik, pengawasan efektif, dan penegakan hukum yang konsisten, kekuasaan—di tingkat mana pun—cenderung disalahgunakan.
Solusinya bukan kembali ke sentralisme Orde Baru. Itu justru mengkhianati demokrasi. Yang dibutuhkan adalah penguatan pengawasan berbasis transparansi digital, keterlibatan aktif warga dan pers lokal, pembinaan serius aparatur kelurahan dan desa, serta penegakan hukum yang tidak pandang jabatan.
Indonesia telah berhasil mendesentralisasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya jauh lebih berat: mendesentralisasikan integritas. Tanpa itu, otonomi daerah hanya akan memindahkan masalah dari pusat ke pinggiran—dari istana ke kelurahan.
Otonomi daerah sejatinya bukan sekadar pemindahan kewenangan dari pusat ke daerah, melainkan pemindahan tanggung jawab moral dalam mengelola kekuasaan. Ketika korupsi justru tumbuh subur di tingkat kelurahan dan desa, itu menandakan bahwa demokrasi belum sepenuhnya berakar pada etika pelayanan publik. Tanpa integritas, otonomi hanya akan melahirkan penguasa-penguasa kecil yang jauh dari semangat reformasi. Karena itu, masa depan otonomi daerah tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan oleh keberanian negara dan masyarakat untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Di sanalah otonomi menemukan makna sejatinya.***