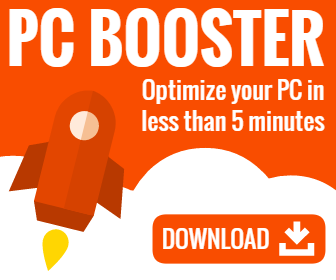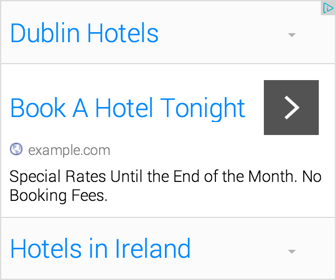Oleh: Indria Febriansyah
Pernyataan Pandji Wicaksono dalam acara Mens Rea di Netflix yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “penculik” telah memantik polarisasi publik. Pro dan kontra tak terelakkan. Namun polemik ini sesungguhnya bukan soal selera humor atau kebebasan berekspresi semata, melainkan menyentuh persoalan yang lebih mendasar: cacat logika berpikir dalam memahami hubungan antara individu, negara, dan sejarah kekuasaan.
Masalah utama dari pernyataan tersebut bukan pada kritiknya, melainkan pada kesalahan atribusi tanggung jawab. Pandji secara sadar atau tidak telah menggeser tindakan negara menjadi kesalahan personal seorang prajurit, lalu membingkainya dalam format komedi. Inilah yang membuat pernyataan tersebut bukan sekadar opini, melainkan distorsi sejarah yang menyesatkan publik.
Negara Tidak Bertindak Secara Personal
Pada periode 1997–1998, Indonesia masih berada dalam struktur negara Orde Baru. Keamanan nasional sepenuhnya berada di bawah komando ABRI, belum ada pemisahan Polri sebagai institusi sipil mandiri. Dalam sistem tersebut, seluruh operasi keamanan termasuk pengamanan demonstrasi, penanganan kerusuhan, dan pengendalian aktor politik merupakan tindakan negara yang dijalankan melalui rantai komando militer.
Presiden Prabowo Subianto saat itu adalah perwira aktif TNI dan menjabat sebagai komandan satuan. Dalam doktrin militer dan hukum tata negara, seorang prajurit tidak memiliki ruang bertindak secara personal. Ia adalah alat negara (state apparatus) yang menjalankan perintah sah dari atasan dalam struktur komando yang hierarkis.
Dengan demikian, menempelkan label “penculik” secara personal kepada Prabowo berarti mengabaikan fakta bahwa negara bertindak melalui institusinya, bukan melalui kehendak individual. Ini adalah bentuk logical fallacy yang dikenal sebagai false attribution, yakni menyalahkan individu atas keputusan institusional.
Kesalahan Anakronisme Hukum
Kesalahan berikutnya adalah penggunaan standar hukum pasca-Reformasi untuk menilai peristiwa pra-Reformasi. Pandji dan sebagian publik tampaknya lupa bahwa UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum belum lahir ketika peristiwa penculikan aktivis oleh Tim Mawar terjadi.
Faktanya, rangkaian peristiwa tersebut berlangsung antara Juli 1997 hingga Mei 1998, sementara UU kebebasan berpendapat baru disahkan pada 23 September 1998. Artinya, kerangka hukum yang mengatur demonstrasi, kebebasan berekspresi, dan unjuk rasa pada masa itu sangat berbeda dengan hari ini.
Mengadili tindakan negara tahun 1998 dengan norma hukum 2026 adalah anakronisme hukum, kesalahan metodologis yang sering terjadi dalam perdebatan publik. Negara saat itu beroperasi dalam paradigma keamanan dan stabilitas, bukan demokrasi liberal sebagaimana sekarang.
Negara dalam Situasi Krisis Eksistensial
Menjelang runtuhnya Orde Baru, Indonesia berada dalam kondisi yang oleh banyak analis disebut sebagai krisis eksistensial negara. Kerusuhan massal, konflik horizontal, tekanan ekonomi, serta manuver politik elit menciptakan situasi yang oleh aparat keamanan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keutuhan negara.
Dalam konteks seperti itu, aparat keamanan termasuk Tim Mawar diberi mandat untuk mengamankan situasi, aktor, dan jaringan yang dianggap berpotensi memperparah instabilitas. Setuju atau tidak dengan kebijakan tersebut adalah ruang diskursus sejarah dan etika politik. Namun menyederhanakannya menjadi tuduhan kriminal personal adalah bentuk penyederhanaan yang tidak jujur secara intelektual.
Jika logika Pandji diterima, maka seluruh prajurit dan komandan militer di berbagai rezim dunia dapat dituduh secara personal atas setiap tindakan negara, tanpa melihat struktur perintah dan tanggung jawab institusional. Ini jelas logika yang keliru dan berbahaya.
Satire yang Kehilangan Tanggung Jawab
Kebebasan berekspresi adalah pilar demokrasi. Namun kebebasan itu tidak identik dengan kebebasan memelintir fakta. Komedi politik memang sah sebagai bentuk kritik, tetapi tetap memiliki tanggung jawab moral dan intelektual, terutama ketika disiarkan melalui platform global seperti Netflix. Menyebut “Prabowo penculik” tanpa menjelaskan konteks negara, hukum, dan struktur komando bukanlah kritik yang mencerahkan. Itu adalah narasi simplistik yang membunuh kompleksitas sejarah, sekaligus membangun opini publik yang emosional, bukan rasional. Lebih jauh, serangan personal terhadap Presiden Prabowo hari ini dengan membawa tuduhan yang sejatinya merupakan tindakan negara masa lalu juga tidak adil secara etika politik. Demokrasi yang sehat menuntut kritik berbasis kebijakan dan fakta, bukan stigma historis yang dipelintir.
Penutup
Prabowo Subianto muda adalah prajurit negara, bukan aktor sipil bebas. Apa pun yang dilakukan berada dalam kerangka perintah, doktrin, dan kepentingan negara pada masanya. Menyerangnya secara personal hari ini, dengan mengabaikan konteks hukum dan sejarah, adalah kesalahan logika berpikir yang serius.
Jika bangsa ini ingin dewasa dalam berdemokrasi, maka perdebatan publik harus dibangun di atas kejujuran sejarah dan ketepatan logika, bukan komedi yang menyederhanakan negara menjadi sekadar tokoh antagonis di atas panggung.
Demokrasi tidak membutuhkan kebisingan, tetapi kejernihan berpikir.