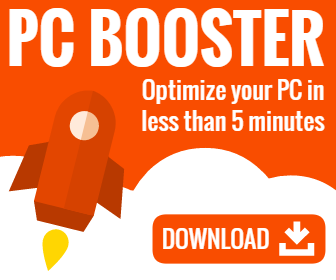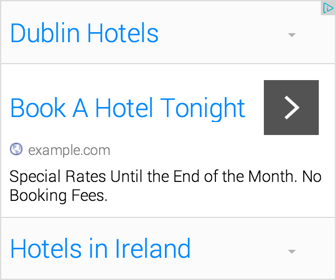Oleh : Chabibi Syaefudin
Pengamat Intelejen UI
Kitabaru.com, Jakarta – Dinamika politik Indonesia di awal 2026 ini menyuguhkan sebuah anomali yang mengusik nalar publik: mengapa penegakan hukum tegas terhadap aktor besar seperti Riza Chalid (RC) oleh Kejaksaan Agung justru direspons dengan serangan bertubi-tubi dari kelompok yang selama ini mengklaim diri sebagai pejuang integritas?
Fenomena yang melibatkan narasi dari “Kelompok 50 yang diisi oleh deretan tokoh vokal seperti Gatot Nurmantyo hingga Said Didu menunjukkan bahwa panggung politik kita sedang tidak baik-baik saja.
Di balik riuh rendah kritik tersebut, tercium aroma operasi intelijen yang sistematis, sebuah upaya penciptaan “Black Swan” (Angsa Hitam) untuk mengguncang fondasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui pelemahan instrumen setia negara, yakni Polri dan Kejaksaan Agung.
Secara teoritis, apa yang kita saksikan saat ini adalah perwujudan dari strategi Subversi dan Agitprop (Agitasi dan Propaganda). Dalam kacamata intelijen, kelompok ini tidak lagi berperan sebagai oposisi konstruktif, melainkan bergeser menjadi Agent of Influence yang digerakkan oleh kepentingan logistik besar yang sedang terdesak.
Jika kita menilik ke belakang, irisan historis mereka sebagai eks pendukung Prabowo-Hatta menjadi titik temu di mana hubungan dengan RC terbangun.
Kekecewaan mereka terhadap langkah pragmatis Prabowo yang berkoalisi dengan pemerintahan sebelumnya bukan didasari oleh idealisme, melainkan ketakutan akan hilangnya perlindungan politik bagi jejaring bisnis RC.
Kini, ketika negara benar-benar “menyikat” simpul-simpul kekuasaan tersebut, serangan balik dilancarkan melalui metode False Flag Operation, di mana isu reformasi birokrasi diputarbalikkan menjadi narasi pembangkangan institusi.
Serangan terhadap Polri dan Kapolri melalui isu penolakan transformasi posisi Polri di bawah kementerian merupakan puncak dari taktik Divide et Impera modern. Dengan mengembuskan stigma negatif bahwa Polri melakukan “pembangkangan” atau mbalelo terhadap Presiden, kelompok ini sedang berupaya memutus urat nadi kepercayaan antara Panglima Tertinggi dan alat pengamannya.
Dalam teori Institutional Realism, stabilitas sebuah rezim sangat bergantung pada soliditas hubungan antara kepemimpinan sipil dan aparat keamanan.
Ketika Polri dituduh membuat “tim tandingan” reformasi, tujuannya bukan untuk memperbaiki institusi, melainkan menciptakan friksi horizontal dengan TNI dan memperlemah wibawa Kapolri di mata Presiden. Ini adalah upaya menciptakan kelumpuhan internal agar energi pemerintah habis untuk memadamkan “api di dalam sekoci” sendiri, sementara aktor intelektual di balik layar mencari celah untuk melepaskan diri dari jerat hukum.
Lebih jauh lagi, keberadaan figur-figur seperti mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di dalam lingkaran tertentu harus dibaca dalam kerangka Fifth Column atau “Kolom Kelima”. Teori ini menjelaskan adanya elemen di dalam atau di dekat kekuasaan yang secara sadar atau tidak menjadi “duri dalam daging”, berfungsi sebagai operator yang menjaga kepentingan lama agar tetap bercokol.
Operasi ini tidak hanya bersifat fisik seperti kegagalan aksi massa Agustus 2025 yang menargetkan pembakaran simbol-simbol negara namun kini berevolusi menjadi serangan asimetris melalui media sosial. Penggelontoran dana besar untuk membiayai buzzer adalah bentuk investasi politik RC untuk mengonstruksi realitas palsu, di mana penegak hukum yang jujur dicitrakan sebagai musuh rakyat, dan koruptor dicitrakan sebagai korban kriminalisasi.
Puncak dari skenario ini adalah persiapan munculnya fenomena Black Swan. Merujuk pada pemikiran Nassim Nicholas Taleb, Black Swan adalah peristiwa langka yang tak terprediksi namun memiliki dampak ekstrem yang menghancurkan. Kelompok 50 dan penyokong logistiknya sedang menanti—atau lebih tepatnya menciptakan—kondisi tersebut.
Jika de-legitimasi terhadap Polri dan Kejaksaan Agung berhasil menciptakan kekosongan otoritas atau mosi tidak percaya di tingkat akar rumput, maka stabilitas nasional akan runtuh dalam sekejap. Dalam situasi kacau itulah, posisi tawar politik akan bergeser, dan kebebasan bagi aktor-aktor seperti RC menjadi komoditas barter yang mungkin terjadi.
Presiden Prabowo harus waspada bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak di jalanan, melainkan mereka yang mampu membelokkan opini publik melalui narasi yang seolah-olah akademis dan patriotik, namun berhulu pada kepentingan sempit satu individu
. Negara tidak boleh kalah oleh orkestrasi “Angsa Hitam” yang dirancang di ruang-ruang gelap. Konsolidasi antara Presiden, Kejaksaan Agung, dan Polri harus diperkuat melampaui sekat-sekat isu sektoral. Jika instrumen penegak hukum ini berhasil dilemahkan atau dibenturkan, maka yang runtuh bukan sekadar citra satu atau dua institusi, melainkan marwah negara hukum Indonesia di tengah ambisi besar menuju kemajuan global.***