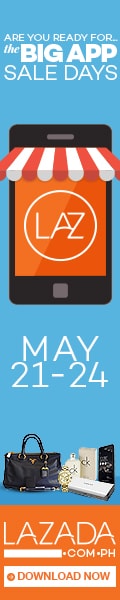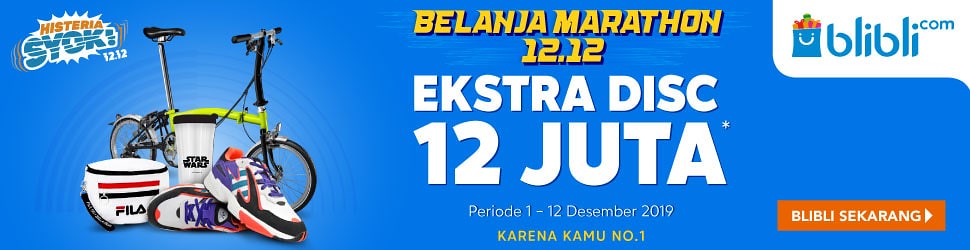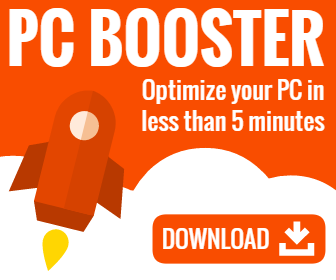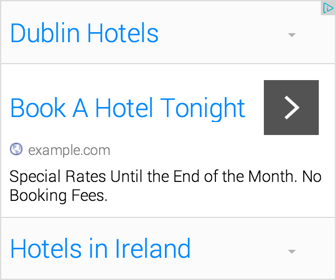Oleh: Dr. Azasi Hasan, S.E., M.M.
Pendahuluan
Kasus mega korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung mencatat sejarah kelam dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu aspek paling kontroversial adalah masalah perhitungan kerugian lingkungan yang mencapai Rp 271 triliun.
Kerusakan lingkungan akibat tambang rakyat atau PETI digunakan sebagai dasar pertama, untuk menjerat para terdakwa dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dan korupsi sesuai pasal 2, 3 dan 18 UU Tipikor dan pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.
Kerugian negara dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 diumumkan pertama kali pada 19 Februari 2024 oleh Kejaksaan Agung dan Prof. Bambang Hero Saharjo. Di mana pada saat itu, sudah ada sekitar 10 orang tersangka. Seolah pengumuman ini menjadi legitimasi hukumnya.
Namun, perhitungan ini tidak hanya bermasalah dari sisi validitas metodologi, tetapi juga dari sudut pandang hukum, ekonomi, bisnis, sosial, dan keamanan. Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Budi Wasis Haryanto sebagai akademisi telah dijadikan alat pembenaran yang ditunggangi keilmuannya oleh penyidik Kejaksaan Agung, untuk memaksakan kriminalisasi terhadap para terdakwa.
Mereka seharusnya memiliki etika keilmuan, hati nurani dan menyadari bahwa yang mereka hitung hanyalah potensi kerugian lingkungan, bukan kerugian nyata dan pasti (potensi) yang memenuhi unsur dalam tindak pidana korupsi. Mereka harus bertanggung jawab, kalau tidak di dunia ini ya nanti di akhirat. Bahwa mereka telah berdosa ikut serta bersama-sama mengkriminalisasi para terdakwa dan keluarganya.
Dan hal ini, pastinya dicatat oleh “jaksa malaikat”, untuk menuntut pertanggung jawaban penggunaan keahlian dan keilmuan dilihat dari asas manfaat dan mudaratnya.
Perspektif Hukum: Perhitungan yang Cacat dan Melanggar Prinsip Pidana
Perhitungan kerugian lingkungan merupakan proses kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin, melibatkan aspek ekonomi, ekologi, dan hukum. Berbagai ahli memiliki pandangan beragam mengenai metodologi yang tepat untuk menghitung kerugian tersebut.
Dari perspektif hukum, perhitungan kerugian lingkungan harus didasarkan pada data yang valid dan metode yang transparan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya, sehingga perhitungan yang digunakan dalam kasus lingkungan hidup harus memenuhi standar tersebut.
Di samping itu dalam hukum pidana, suatu tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti. Perhitungan kerugian lingkungan dalam kasus ini tidak memenuhi unsur tersebut karena hanya merupakan estimasi potensi, bukan fakta hukum yang sah.
Secara hukum, Prof. DR Bambang Hero Saharjo maupun Prof DR Budi Wasis tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kerugian lingkungan. Kewenangan, tugas dan tanggung jawab menetapkan angka kerugian lingkungan ada pada lembaga negara yang berwenang, seperti:
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) – melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan dan Rehabilitasi dalam konteks perhitungan pemulihan ekosistem.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – jika dikaitkan dengan kerugian keuangan negara akibat dampak lingkungan.
3. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) – dalam konteks audit terhadap kebijakan tata niaga.
4. Lembaga peradilan (pengadilan) – yang memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah suatu perhitungan kerugian valid dan dapat dijadikan dasar hukum.
Sedangkan mereka berdua tidak memiliki kompetensi dan kewenangan, karena:
1. Bukan Auditor Resmi Negara: Mereka berdua adalah akademisi dari IPB yang memiliki keahlian dalam analisis lingkungan, tetapi tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan nilai kerugian lingkungan sebagai dasar hukum pidana korupsi.
2. Ahli Hanya Memberi Pendapat, Bukan Menetapkan: Dalam sistem hukum, seorang ahli hanya boleh memberikan pendapat ilmiah, tetapi angka yang dijadikan dasar tuntutan harus ditetapkan oleh lembaga berwenang.
3. Metodologi Tidak Transparan: Perhitungan yang dilakukan tidak menggunakan standar baku yang jelas dan belum diverifikasi oleh lembaga negara yang bertanggung jawab atas penilaian kerusakan lingkungan.
4. Mengabaikan Prinsip Pemulihan (Restorative Justice): Dalam hukum lingkungan, pendekatan yang digunakan bukan hanya menghitung kerugian, tetapi juga potensi pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi.
Lantas, dengan penyidik meminta hasil perhitungan kerugian lingkungan diatas menjadi satu bagian dari perhitungan kerugian negara oleh BPKP menjadi sah dan legal? Tentu saja jawabnya, tidak serta merta menjadi sah secara hukum karena BPKP bukan lembaga yang berwenang seperti KLHK dan tidak kompeten dalam metodologi perhitungan kerugian lingkungan yang sah dan dapat diuji validitasnya.
– BPKP adalah lembaga pengawasan keuangan dan pembangunan yang tugas utamanya adalah mengaudit kebijakan keuangan dan administrasi pemerintahan. BPKP tidak memiliki mandat utama dalam penilaian kerusakan lingkungan karena hal ini merupakan kewenangan KLHK dan lembaga terkait lainnya. BPKP bisa menghitung kerugian keuangan negara, tetapi tidak memiliki otoritas utama dalam menilai kerugian lingkungan. Kerusakan lingkungan bersifat multidimensi, sehingga perhitungannya harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten di bidang lingkungan, seperti KLHK.
– Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengatur bahwa penilaian dampak lingkungan harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, bukan oleh auditor keuangan.
– UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penghitungan dan penentuan sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan harus berbasis pada kajian ilmiah yang dilakukan oleh KLHK.
– Kerusakan lingkungan yang masih bisa dipulihkan tidak bisa langsung dikategorikan sebagai kerugian negara, karena ada prinsip environmental recovery (pemulihan lingkungan) yang memungkinkan nilai tersebut berkurang atau bahkan dihilangkan.
Perspektif Ekonomi Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Metodologi Penelitian yang Dipertanyakan?
Perhitungan kerusakan lingkungan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman bagi instansi terkait dalam menilai dan menghitung besarnya kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Salah satu peraturan utama adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Peraturan ini menetapkan panduan bagi instansi lingkungan hidup pada tingkat pusat dan daerah untuk menghitung kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup, serta formula penghitungan sebagai dasar mengajukan ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Artinya bukan pedoman untuk menghitung kerusakan akibat tambang yang IUP nya sudah diterbitkan dan ada jaminan reklamasi dan program reklamasi yang dilakukan secara bertahap. Program reklamasi ini juga bukan berarti mengembalikan lingkungan seperti semula, tetap mereklamasi melalui program pemanfaatan lahan bekas tambang, dalam bentuk industri perkebunan (misal sawit), tempat rekreasi seperti air jangkang (taman dan kebun binatang) dan bentuk lainnya.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan kerangka kerja untuk penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan. Peraturan ini menekankan prinsip ultimum remedium dan penerapan sanksi administratif dalam penanganan kasus-kasus lingkungan.
Mengenai metodologi perhitungan yang dilakukan oleh Prof. Bambang Hero Saharjo dan timnya dalam kasus tata niaga timah, mereka menggunakan pendekatan yang sesuai dengan Permen LH No. 7 Tahun 2014. Prof. Bambang Hero menjelaskan bahwa perhitungan tersebut dilakukan olehnya sebagai ahli kerusakan lingkungan dan/atau ahli valuasi ekonomi, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Hasil perhitungan mereka menunjukkan total kerusakan lingkungan sebesar Rp271,07 triliun, yang terdiri dari:
– Biaya Kerugian Lingkungan (Ekologis): Rp183,7 triliun
– Biaya Kerugian Ekonomi Lingkungan: Rp74,4 triliun
– Biaya Pemulihan Lingkungan: Rp12,1 triliun
Sejumlah pertanyaan kritis pun muncul, setelah mendengar di persidangan sebagai saksi ahli tidak mampu menjelaskan, membuktikan keabsahan dan kebenaran laporannya. ketika ditanya dia menjawab “Maaf Yang Mulia.. Malas Jawabnya”. Sementara bermula dari hitungannnya telah mengkriminalisasi sejumlah terdakwa di kasus tata niaga timah. Apa pertanyaan kritis itu;
Bagaimana luas kerusakan ditentukan?
– Apakah menggunakan citra satelit real-time gratisan dapat memberikan skala luasan dengan pembandingan periode yang benar?
– Apakah benar-benar membedakan tambang legal dan ilegal, atau asal pukul rata?
– Seperti kata Ahok: Apakah benar-benar kerugian dampak lingkungan yang terjadi dalam periode 2015 – 2022? Apa kerusakan sejak jaman Belanda dihitung?
Bagaimana nilai kerugian dihitung?
– Apakah menggunakan pendekatan nilai pemulihan ekosistem yang benar?
– Apakah angka Rp 271 triliun itu termasuk “kerugian asumtif” tanpa memperhitungkan kontribusi tambang rakyat terhadap perekonomian Bangka Belitung?
Mereka berdua sangat mengagumkan karena berhasil menyelesaikan kajian ini dan bahkan menulisnya menjadi laporan kerugian lingkungan mengandung konsekuensi hukum hanya dalam waktu beberapa bulan. Konon hanya dalam waktu 3 – 4 bukan hanya dengan beberapa kali ke lapangan.
Padahal kalau kita bandingkan dengan perhitungan kerugian lingkungan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Deepwater Horizon (2010, Amerika Serikat)
– Nilai kerugian: USD 17 miliar (~Rp 260 triliun)
– Metode:
– Studi ekologi jangka panjang
– Pemodelan dampak lingkungan berbasis GIS
– Monitoring biota laut selama lebih dari lima tahun
– Jumlah ahli: Ratusan ilmuwan lingkungan, ahli geospasial, ekonom lingkungan, dan lembaga independen
– Durasi perhitungan: Bertahun-tahun
2. Lumpur Lapindo (2006, Indonesia)
– Nilai kerugian: Rp 10 triliun
– Metode:
– Kajian hidrogeologi
– Studi sedimentasi dan pemetaan dampak sosial-ekonomi
– Jumlah ahli: Tim multidisiplin termasuk geolog, ekonom lingkungan, dan ahli kebencanaan
– Durasi perhitungan: Bertahun-tahun
3. Kasus Timah Bangka Belitung (2024, Indonesia)
– Nilai kerugian: Rp 271 triliun
– Metode: Tidak sepenuhnya transparan
– Apakah menggunakan model ekosistem jangka panjang?
– Apakah dampak sosial-ekonomi diperhitungkan?
– Jumlah ahli: Tidak banyak informasi tentang siapa saja yang terlibat selain dua nama utama
– Durasi perhitungan: Beberapa bulan
Perspektif Ekonomi: Distorsi Angka dan Dampaknya terhadap Industri
Dari sudut pandang ekonomi, perhitungan Rp 271,07 triliun mencerminkan overestimasi yang tidak realistis dan berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, karena:
1. Mengkriminalisasi kebijakan sah PT.Timah Tbk dalam skema Business Judgement Rules dalam Business Critical Aset.
– Kriminalisasi program pengamanan aset vital dengan penerapan kemitraan ekonomi kerakyatan dengan membina tambang rakyat atau PETI karena regulasi yang tidak kunjung ada dan lemahnya pengawasan pertambangan timah.
– Program Pemovit dan Kemitraan PT Timah Tbk adalah strategi business critical asset untuk menjaga kelangsungan industri timah. Jika ada kekurangan dalam implementasi kebijakan ini, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata atau administratif, bukan dijadikan objek kriminalisasi.
– Program ini juga, memberikan trikledown efect di mana sektor tambang timah menjadi growth pole economy bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
2. Mengabaikan Kontribusi Ekonomi dari Industri Timah
– Ekspor timah berkontribusi Rp 85 triliun terhadap devisa negara. PT Timah juga telah membayar royalti dan pajak sebesar Rp 7,021 triliun.
– Angka Rp 271 triliun tidak memperhitungkan manfaat ekonomi dari industri ini, sehingga memberikan gambaran yang bias dan tidak seimbang.
3. Dampak terhadap PDRB Bangka Belitung
– Pada 2023, ekonomi Babel tumbuh 4,38%, namun pada 2024 turun drastis menjadi 0,77%, yang bertepatan dengan kriminalisasi tata niaga timah.
– Investor dan pelaku usaha menjadi takut berinvestasi, menciptakan stagnasi ekonomi daerah.
Perspektif Sosial dan Keamanan: Krisis Akibat Kriminalisasi Berlebihan
1. Pengangguran dan Kemiskinan
Ribuan pekerja tambang rakyat kehilangan mata pencaharian akibat ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh kasus ini. Bahkan ikut, berdampak pada para petani sawit dan PHK pegawai pabrik PKS milik para pengusaha smelter swasta karena penyitaan oleh kejaksaan.
2. Potensi Instabilitas Sosial
Kriminalisasi ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum.
3. Meningkatnya Aktivitas Ilegal
Dengan tersendatnya industri legal, tambang ilegal semakin marak, menciptakan masalah baru yang lebih sulit dikendalikan, terutama dari sisi penyelundupan.
Kritik terhadap Prof. Bambang Hero dan Prof. Budi Wasis
Sebagai akademisi, seharusnya mereka bersikap objektif dan berpegang pada prinsip ilmiah, bukan menjadi alat pembenaran bagi kriminalisasi hukum. Beberapa kelemahan utama dalam perhitungan mereka:
1. Menggunakan Perhitungan Potensial, Bukan Kerugian Aktual
Perhitungan ini mengasumsikan bahwa semua lahan yang digunakan dalam program kemitraan telah rusak permanen, tanpa mempertimbangkan reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukan.
2. Tidak Mempertimbangkan Faktor Manfaat dan Mitigasi
Setiap industri memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki kontribusi ekonomi dan program pemulihan.
3. Berperan dalam Justifikasi Kriminalisasi
Perhitungan ini digunakan sebagai dasar hukum yang tidak adil, yang mengakibatkan banyak individu dikriminalisasi tanpa dasar yang kuat.
Pendapat Prof. Sudarsono:
Prof. Sudarsono, salah satu pakar lingkungan terkemuka di Indonesia, mengkritik keras metodologi perhitungan ini, karena mengandung banyak kelemahan mendasar yang membuatnya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam kasus pidana korupsi.
– Akademisi seharusnya tidak membiarkan ilmunya digunakan untuk kepentingan politik atau kriminalisasi yang tidak berdasar.
– Perhitungan lingkungan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, bukan hanya menonjolkan angka besar untuk menciptakan efek kejut.
– Jika perhitungan kerugian lingkungan digunakan sebagai dasar hukum pidana, harus ada standar baku dan metodologi yang diakui secara akademis dan hukum.
Kesimpulan: Hentikan Kriminalisasi, Fokus pada Solusi yang Berkeadilan
Perhitungan kerugian lingkungan Rp 271 triliun dalam kasus timah tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, tidak sah secara hukum, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi serta sosial di Babel. Seharusnya:
– Metode perhitungan harus berbasis data aktual, bukan asumsi potensi yang berlebihan.
– Hukum harus berorientasi pada keadilan, bukan sekadar angka bombastis untuk kriminalisasi.
– Pemerintah harus memperbaiki regulasi tata niaga timah agar tidak menjadi sumber penyalahgunaan hukum.
Akademisi seperti Prof. Bambang Hero dan Prof. Budi Wasis harusnya sadar bahwa keahlian keilmuan yang mereka miliki seharusnya digunakan untuk keadilan dan keberlanjutan, bukan sebagai alat politik yang menghancurkan kehidupan banyak orang.
Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya industri timah yang mati, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga akan runtuh.
Coba kita renungkan, bagaimana nasib para terdakwa yang oleh hakim banding Pengadilan Tinggi Jakarta diperberat, hukumannya atas nama rasa keadilan masyarakat dan kerugian negara yang sangat besar.
Padahal perhitungan kerugian negaranya diragukan keabsahannya baik oleh BPKP maupun Prof. Dr Bambang Hero dan Tim. Sungguh ironis dan menyedihkan.
Harapan tertumpu pada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan untuk meluruskannya dengan memberikan putusan kasasi secara seadil-adilnya dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas peranan masing-masing terdakwa dan kepastian hukum.
Dimana bebas dari tekanan politik dan opini publik yang sejak awal penanganan kasus dibangun persepsinya oleh Kejaksaan Agung melalui buzzer profesionalnya untuk mengkriminalisasi. (*)
Publisher: Syafrudin Budiman SIP